Adat Sebagai Suaka Jiwa: Larvul Ngabal & Makna Kemanusiaan dalam Cermin Buta Negara
Oleh:
M Akhwandany Uwar
(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta & Founder D’Arutala Community)
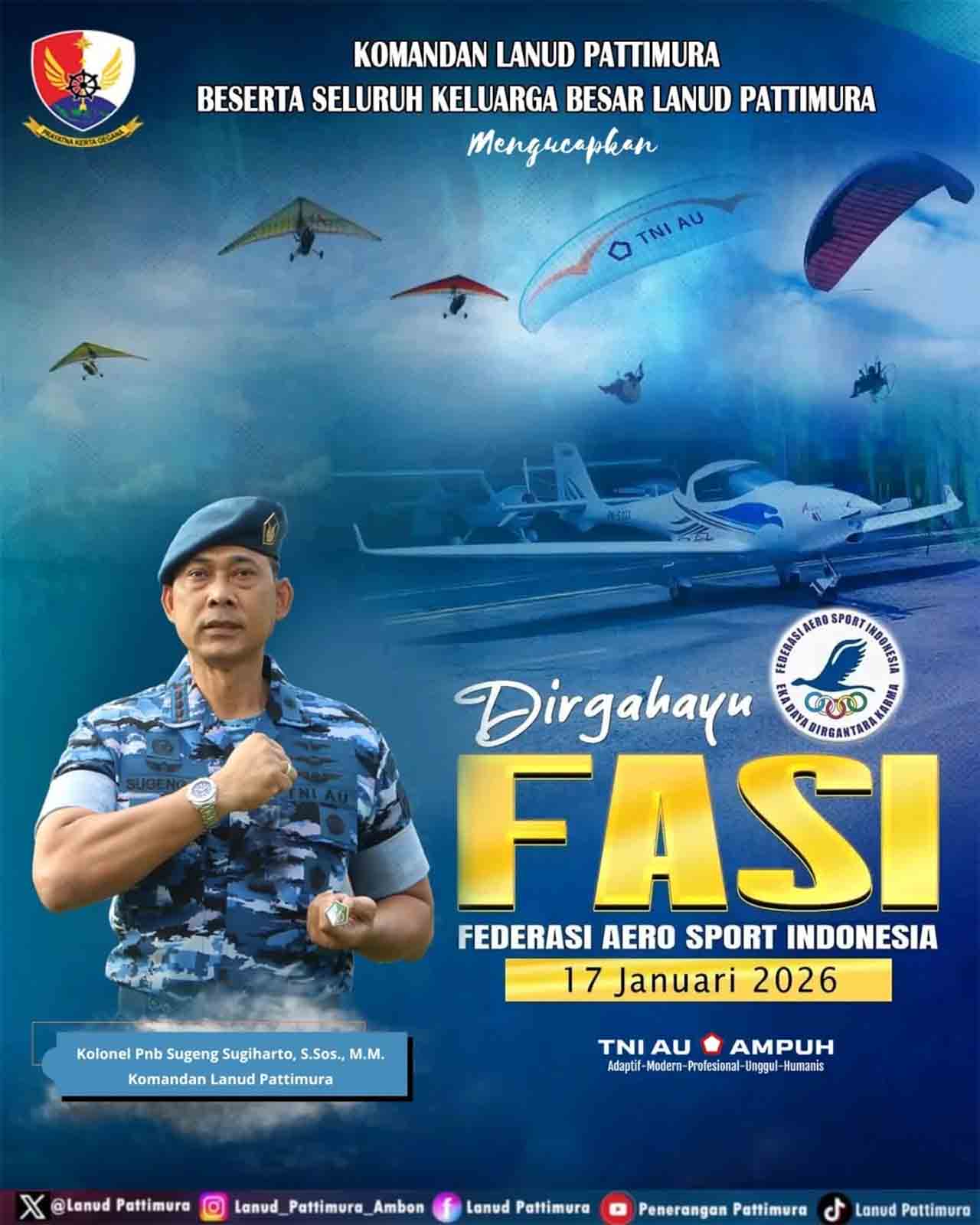

Ketika negara sibuk merumuskan kebijakan berbasis rasional-modern yakni kebijakan yang didasarkan pada aturan yang tertulis dan prinsip-prinsip hukum formal. masyarakat adat di pelosok Nusantara diam-diam menunjukkan bagaimana hukum bisa tumbuh dari tanah, hidup dalam tubuh asyarakat, dan berdenyut dalam nadi budaya.
Salah satu cermin yang memantulkan itu secara terang adalah Larvul Ngabal, sistem hukum adat masyarakat Kei di Maluku Tenggara. Di tengah runtuhnya tatanan formal akibat konflik 1999, Larvul Ngabal bukan hanya bertahan, tetapi tampil sebagai perangkat resolusi konflik yang lebih bermoral, lebih partisipatif, dan lebih manusiawi.
Fungsi hukum tidak semata soal tegaknya pasal demi pasal, tetapi bagaimana ia menjadi pelindung martabat. Dalam konteks ini, Larvul Ngabal adalah suaka jiwa, payung bagi mereka yang terpinggirkan, mereka yang “setengah mati” dalam istilah lokal nit, dan juga mereka yang hidup di batas-batas keadilan formal. Adat tidak berhenti pada struktur kekuasaan, tetapi hidup dalam lagu, ritus, dan ingatan kolektif. Ia bekerja sebagai sistem moral yang tidak mengenal inkonsistensi atau ketidakkonsistenan tafsir sebagaimana hukum negara.
Saya melihat bahwa dalam kerangka filsafat, ungkapan Taflur Nit, Itsob Duad “menghibur orang mati, menyembah Tuhan”, menjadi pusat spiritual dari Larvul Ngabal. Kalimat ini tidak hanya bermakna ritualistik, tetapi adalah etika dasar hukum yang menyatukan rasa, akal, dan iman. Ia mewajibkan masyarakat untuk tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memulihkan relasi.
Inilah wajah hukum yang lebih dalam, lebih lunak, dan karenanya lebih kuat dalam membasuh luka sosial.
Sayangnya, negara justru buta terhadap potensi ini. Pemerintah sering kali menganggap hukum adat sebagai ornamen kultural belaka, atau sebagai simbol identitas etnis yang patut dihormati tapi tidak perlu diadopsi dalam kebijakan formal. Padahal, jika negara bersedia bercermin lebih jujur, banyak nilai dalam hukum adat seperti Larvul Ngabal justru bisa menjadi model etik dan procedural dalam menyusun regulasi yang lebih manusiawi. Sebaliknya, absennya pengakuan structural terhadap sistem seperti ini menunjukkan kegagalan negara dalam membaca kenyataan sosial secara mendalam.
Dalam tulisan ini, justru yang menggantung dan terus menagih perenungan bagi saya adalah sebuah pertanyaan mendasar: mengapa model lokal seperti Larvul Ngabal tidak menjadi rujukan sistemik dalam desain kebijakan resolusi konflik nasional? Bukankah kecepatan, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik 1999 seharusnya membuka mata negara bahwa tidak semua solusi datang dari peradaban birokrasi.

Karenanya, melalui tulisan ini saya ingin menegaskan bahwa hukum adat bukan semata-mata jejak historis yang usang, melainkan modal sosial dan kultural yang sah untuk masa depan. Larvul Ngabal adalah contoh konkret bahwa hukum bisa menjadi tempat berteduh jiwa, bukan sekadar instrumen pengendalian, tetapi menjadi ruang pemulihan terhadap butanya negara. (*)


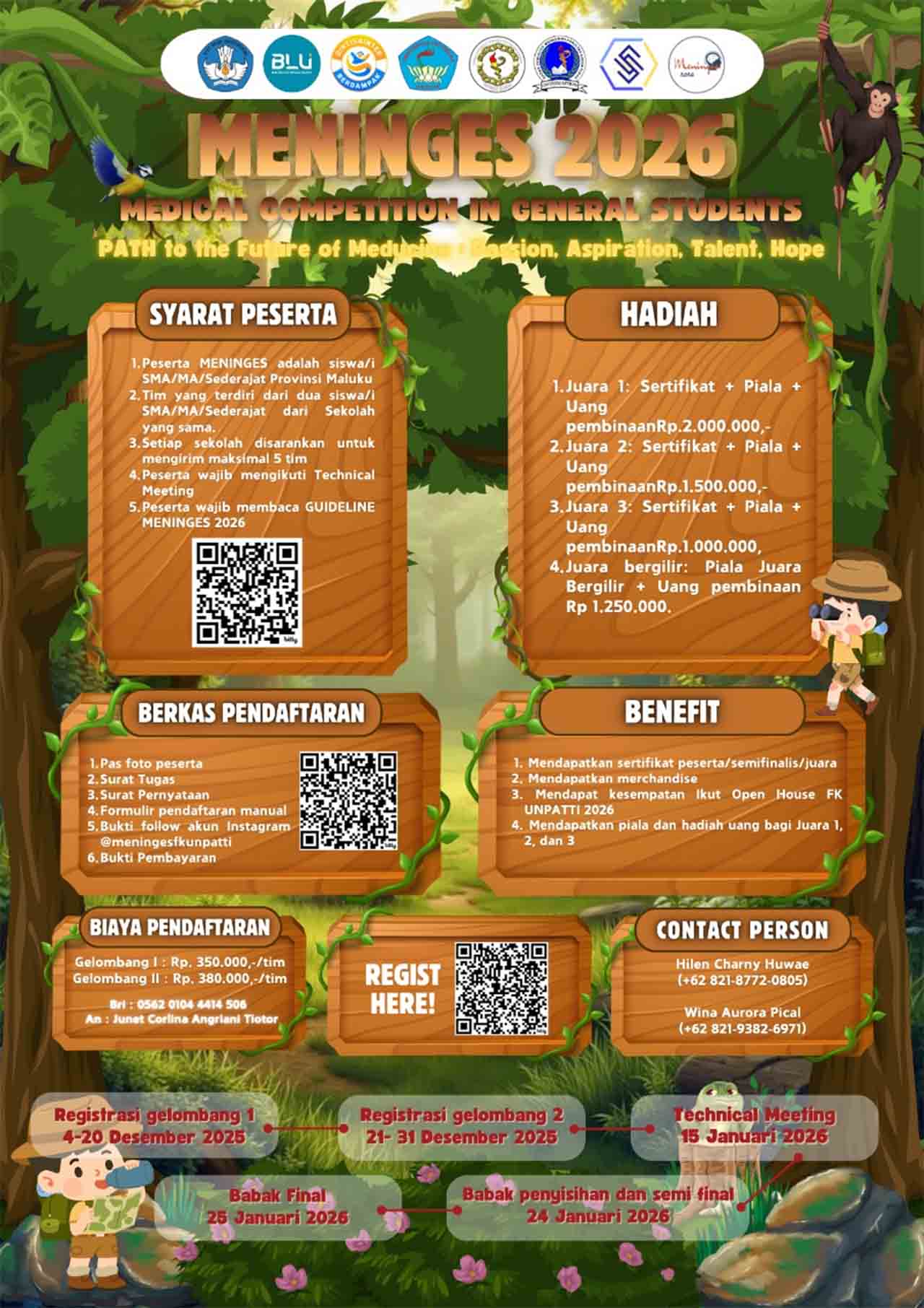





Tinggalkan Balasan